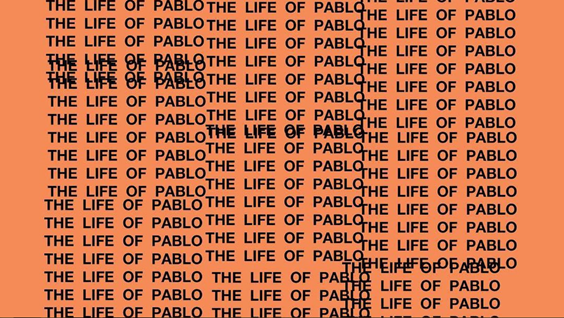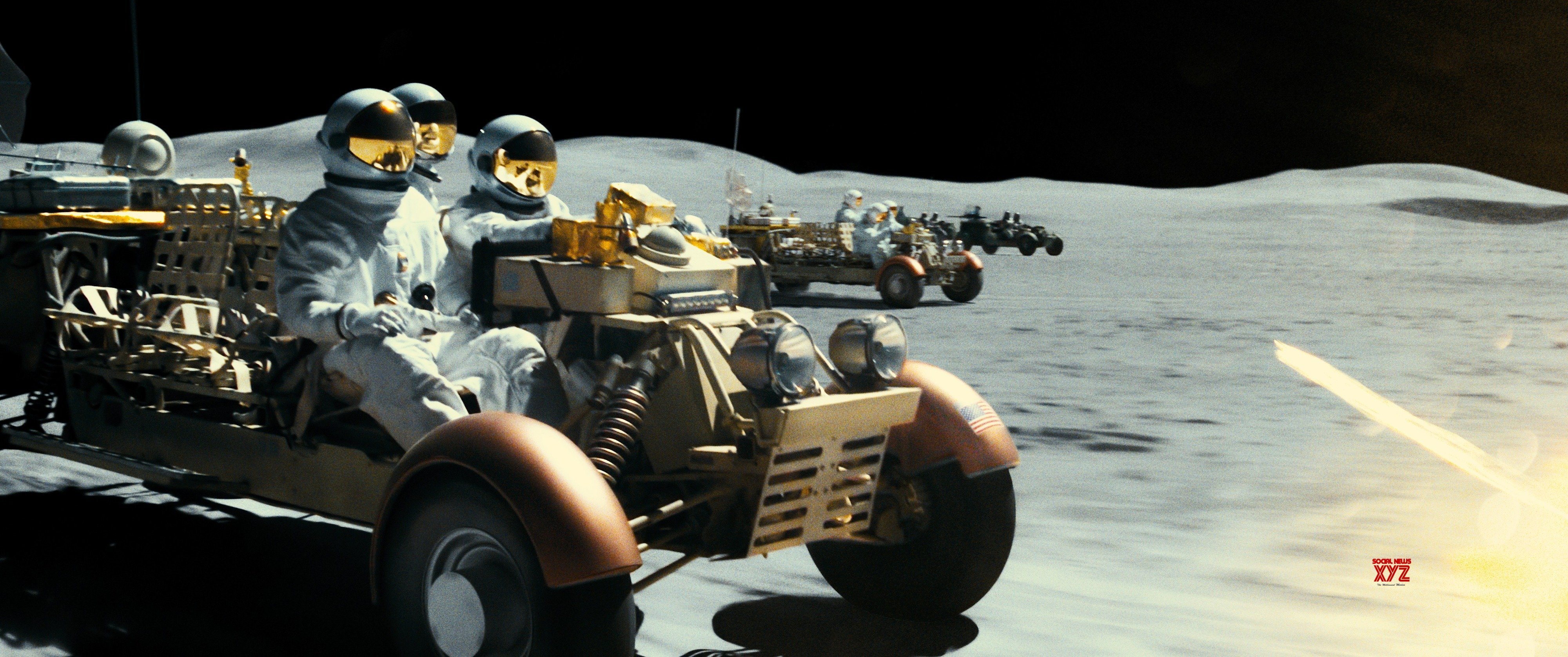The Shining adalah mahakarya. Dia adalah 2,5 jam adaptasi Stephen King yang tidak setia, dan membuat sang penulisnya marah. Bukan tanpa sebab, visi Kubrick dan King memang tidak sejalan. Memang bukan pengetahuan yang baru buat para penggemar film, tetapi gue rasa cukup untuk mengawali review ini.
Novel Doctor Sleep dirilis pada tahun 2013, digadang-gadang sebagai “sekuel” dari The Shining dengan menyoroti kisah Danny Torrance dewasa yang sudah tidak sering dipanggil “Doc lagi. Kata “sekuel” perlu dipetikgandakan karena beberapa sebab, utamanya tidak ada nuansa horor yang mengungkap. Bukan berarti Doctor Sleep tanpa misteri, tanpa keseruan, hanya saja mungkin bukan yang diharapkan dari klaustrofobia di Hotel Overlook.
Film dibuka dengan adegan sudut pandang angkasa, mengingatkan akan pembuka The Shining dengan font warna birunya yang agak menyakitkan mata. Bagian prolog ini menyimpan referensi lain seperti Doc bersepeda mengelilingi lorong berkarpet jingga, dan berhenti di depan kamar 237. Sorot per sorot diabadikan persis, dan berkat menonton ulang di HITS channel jadi sempat menyadari hal ini.
Film ini adalah entitas baru, tetapi sering sekali bikin referensi sana sini. Yang paling ketara terletak di bagian akhir film, yakni kalian dibawa kembali ke dalam Hotel Overlook dengan segala horornya. Uuu, si gadis kembar, wanita telanjang, anggur merah tumpah, labirin bersalju. Semua bagian ini terasa hampir mirip dengan homage yang dibuat Spielberg dalam Ready Player One. Terasa agak sintetis, entah itu karena CGI-nya atau apa.
Ada juga adegan ketika Danny harus bicara empat mata di sebuah ruangan yang menyerupai ruang manager Overlook, tulisan “redrum” yang mirip sekali dengan di The Shining (padahal tidak mesti begitu), transisi dissolve yang jumlahnya tidak dihitung lagi. Agak reaching soal dissolve, tapi tren yang satu ini memang prominen di tahun 70-an akhir hingga 80-an awal.
Omong-omong soal era tersebut, ada satu hal yang benar-benar asik buat ditonton di sini. Itu adalah ketika antagonis utama kita, Rosie si Topi, dimainkan oleh Rebecca Ferguson. Udah, itu aja. That’s the tea.

Ga juga sih.
Di antara kekuatan baru yang diungkap di sini, shiner seperti Rosie si Topi ternyata bisa melacak keberadaan sesama mereka. Adegan ini digambarkan dengan memperlihatkan tubuh dia yang melayang secara astral sembari mencari mangsa baru. Rosie diam di tengah bingkai, sembari bumi menggulirkan diri, memberikan kesan green screen layaknya Jin dan Jun. Dan ini bukan cercaan. Mike Flanagan memberikan sentuhan artistik yang keren buat sekuen ini, dengan membuat subjek terasa diam di tengah kemegahan yang bergerak hanya untuknya saja.
Apa yang datang setelahnya adalah adegan horor yang menarik dan berisi, karena memperlihatkan nuansa untuk karakternya. Adegan horor di sini tidak hanya sekadar didasari oleh insting bertahan hidup. Ada twist menarik yang sehingga memberi dimensi pada ketakutan para tokoh yang bersangkutan. Gue juga suka bagaimana horor yang di sini tidak selalu memiliki nilai mistis. Ada sesuatu yang mengerikan dari teror yang datang dari manusia sendiri. Gue rasanya pernah bilang ini di tulisan sebelumnya, entahlah, tapi yang pasti gue lebih ngeri ketika dua orang ga dikenal datang untuk main-main dengan nyawa keluarga lu (Funny Games) atau ketika lu ga bisa ngenalin diri sendiri akibat LSD (Climax). Gue ga ingin membocorkan banyak, tapi yang pasti Doctor Sleep punya itu, yang bikin gue ga kecewa.
Faktor berhasilnya film ini tidak dipungkiri ada dari casting Ewan McGregor sebagai Danny Torrance. Aktor lain juga tidak kalah menyumbang keberhasilan (sempat kaget ketika melihat Si Raksasa dari Twin Peaks, Bruce Greenwood, sama Jacob Tremblay), tetapi Ewan di sini mengangkat karakter Danny dengan aktingnya. Dia tahu kapan harus menjadi pendiam yang lemah, pendiam yang tangguh, atau pendiam lemah yang tangguh.
“Apa sih maksud lo?”
Cacat cela seorang ayah bakal selalu turun ke anaknya, cepat atau lambat, sedikit atau banyak. Doc adalah seorang alkoholik, bakat yang menurun dari Jack. Di babak pertama, Danny punya sejarah yang disampaikan secara kurang mengenakkan. Beneran kurang mengenakkan karena LSF ternyata memutuskan menyensor kokain dan tubuh wanita telanjang di film D17+. Intinya, film ini berhasil buat Danny sebagai karakter yang punya cela dan dia sadar buat memperbaiki diri, sehingga cerita punya perkembangan yang berarti. Perkembangan ini memuncak di akhir babak kedua, ketika Danny harus menghadapi masa lalunya kembali. Dia tidak sendiri, tetapi sesekali ditemani oleh Tn. Hallorann dalam wujud arwah. Ada dua adegan dialog berdurasi panjang di mana hanya ada Doc dan Dick, memberikan nilai sentimental tersendiri soal figur ayah yang Danny tidak pernah dapat.
Karakter yang dalam juga sempat gue perhatikan dari film Flanagan lainnya, yakni Gerald’s Game (juga adaptasi novel Stephen King). Kedua film punya pondasi karakter utama yang kuat, sehingga gue jadi asik buat mengikuti cerita mereka. Tokoh utama yang ngaro ngidul berkeliling negara juga terasa seperti apa yang terjadi di Firestarter (satu-satunya novel Stephen King yang gue pernah baca). Katanya bakal dibikin film (lagi) sih, cuma kurang tahu juga.
Untuk masalah komedi, film ini punya banyak yang tidak disengaja. Salah satu yang paling ketara adalah kamera memusatkan perhatiannya pada kucing putih bernama Azrael yang bisa meramal kematian seseorang sembari memasang muka sengaknya. Latar waktu dan tempat juga seperti kelinci, melompat ke sana kemari dengan letak yang cukup bikin bingung secara geografis.
Layaknya Glass untuk Unbreakable, Doctor Sleep adalah, well, Doctor Sleep untuk The Shining. Ketika semua misteri terungkap selama bertahun-tahun lamanya baik dari James Dunn ataupun Jack Torrance, tidak ada lagi ketegangan yang benar-benar terbentuk. Glass dan Doctor Sleep hanya vulgar menjadi film “action” dengan premis yang sudah terbentuk di film terdahulu. 150 menitan ini terasa seperti orkestra adu kuat antara siapa yang paling cenayang, dengan menambahkan unsur-unsur cerita yang jauh dari kata menyeramkan secara tradisional. Tidak ada kesalahan dari ini, hanya sedikit memberi peringatan tentang apa yang bisa diharapkan.
Yang bisa kalian harapkan adalah pengalaman menonton yang cukup seru, tidak terlalu neko-neko, dan pastinya dibuat dengan craftmanship yang rapi dari salah satu sutradara horor terbaik di era ini.
Doctor Sleep bukan mahakarya. Dia adalah 2,5 jam nostalgia Stanley Kubrick, tetapi juga adaptasi Stephen King yang setia. Tidak mencoba untuk jadi sempit, tetapi menjangkau hal-hal yang belum pernah dieksplor sebelumnya dengan mengorbankan imersi.